


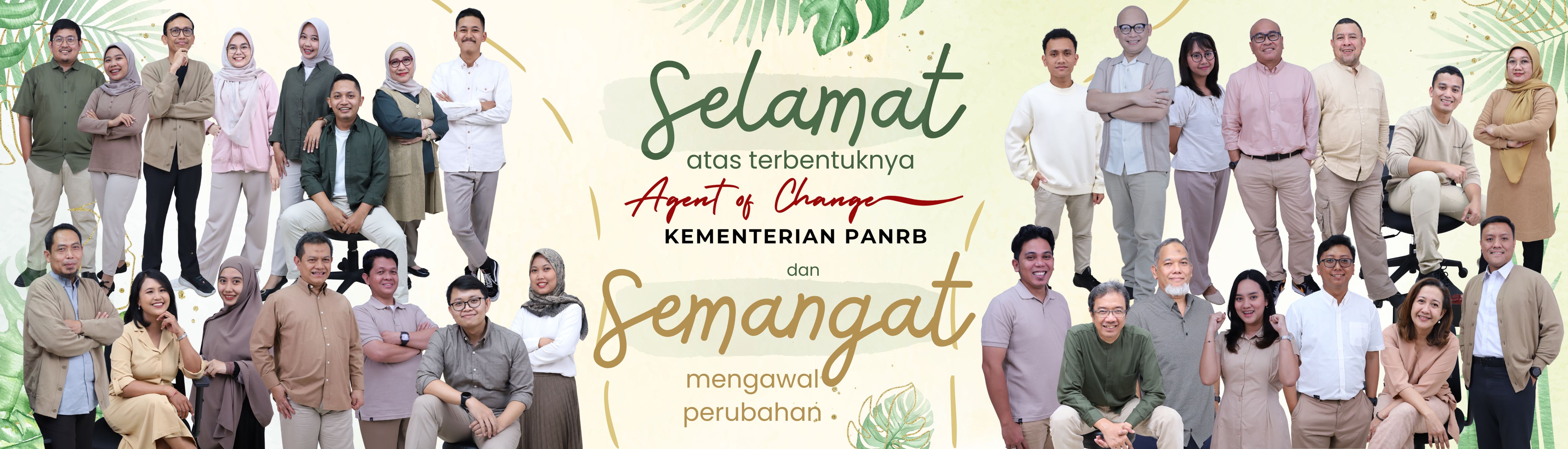
Berita Terbaru
Berita Lainnya
TRANSFORMASI DIGITAL APA ITU DAN PENTINGKAH ?
19 March, 2024
Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi dig...
Selengkapnya
Tingkatkan Kebersamaan Pegawai melalui PANRB Community Fest
29 January, 2024
Acara PANRB Community Fest merupakan rangkaian acara dari ASN Muda Kementerian P...
Selengkapnya
Kekompakan Sesi Foto Agen Perubahan
29 January, 2024
Suasana sesi pemotretan Agen Perubahan berlangsung kompak dan ceria, di Ruang St...
Selengkapnya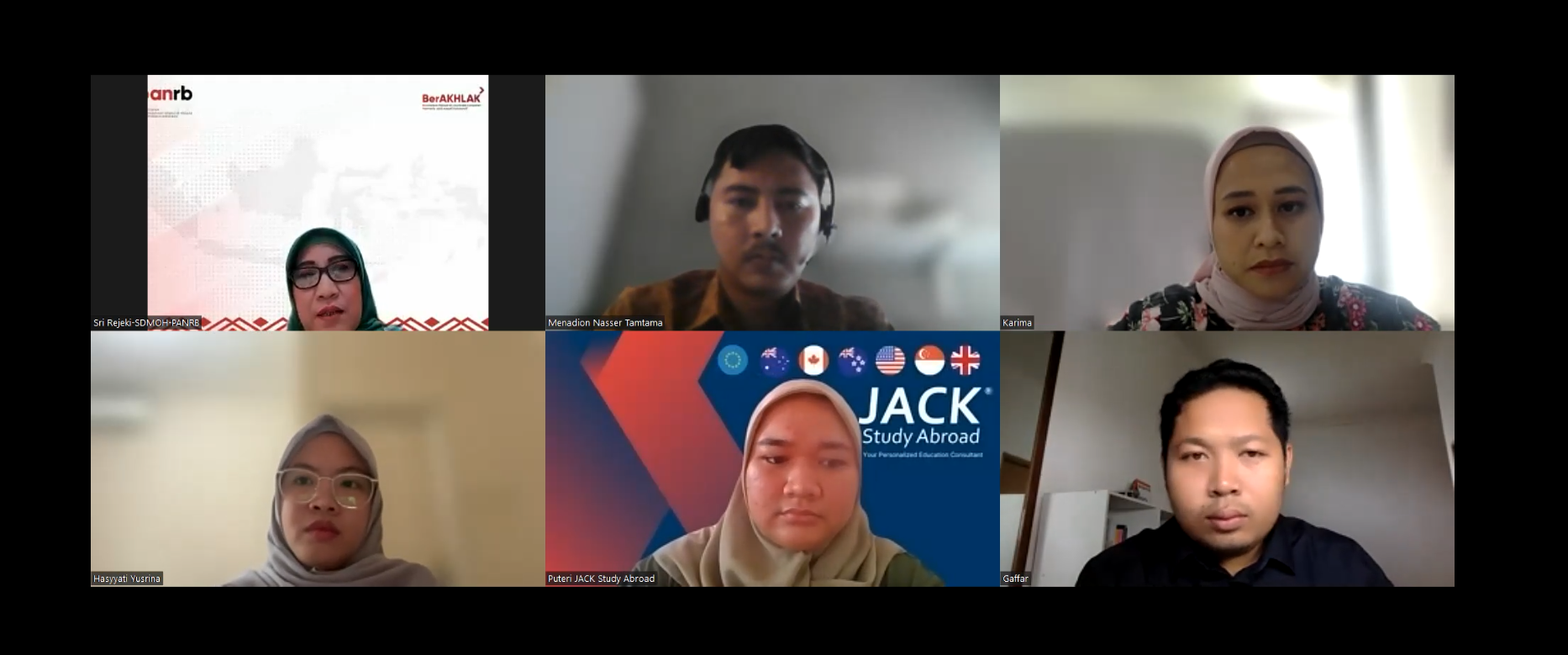
Knowledge Sharing Melanjutkan Pendidikan dengan Beasiswa LPDP
13 January, 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaks...
SelengkapnyaArtikel Terbaru
Artikel Lainnya
PUASA BUKAN ALASAN UNTUK TIDAK BEROLAHRAGA, PANRB RUNNERS GAZZZ !!!
19 March, 2024
Penyelenggaraan “NgabubuRun” yang akan diadakann sabtu mendatang tu...
Selengkapnya
Menyambut HUT Ke-52 KORPRI
26 November, 2023
Jakarta -Tanggal 29 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Pegawai...
Selengkapnya
Pemilu 2024 Menjadi Ujian Netralitas ASN
20 November, 2023
Isu netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN ini kembali mengemuka seir...
Selengkapnya
Menpan RB Targetkan RB Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya
15 March, 2023
Oleh: Ali Akhmad Noor Hidayat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas...
Selengkapnya


